
Pernah suatu saat saya terbayang, sebenarnya apa sih yang membuat Suciwati kala itu begitu mantap menerima pinangan Munir; lelaki yang “sukses” menjadi “buronan” aparat pemerintah karena keberanian level singa dalam mengungkap borok dalam kasus penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Tapi seketika rasa penarasan saya terjawab karena teringat sebuah kalimat, bahwa seorang lelaki bermental singa, tentu layak mendapatkan perempuan yang bermental singa pula. Saya rasa, keduanya memang klop. Laiknya pedang bertemu baju besinya yang saling menjaga, menguatkan, dan mendukung. Kisah Munir dan orang-orang bermental pejuang yang semisal dengannya, memang selalu menarik diungkap dari sisi yang berbeda. Sebagai wanita, tentu kita perlu tertarik untuk menelisik kisah sepak terjang sang istri. Apa yang membuatnya seberani itu bersuamikan lelaki yang namanya –jika boleh dikatakan–, “di-blacklist pemerintah”, karena dianggap membahayakan kaum elite yang haus harta, tahta, dan tentu saja… darah.
“Pahlawan adalah Martir Kebebasan.”
Saya teringat kata-kata Suciwati tentang sang suami, yang diungkapkannya pada bulan April dua tahun silam saat acara peresmian jalan Munir di kawasan Den Haag, Belanda. Ia berujar bahwa suaminya pernah menuturkan, seorang yang pantas disebut pahlawan adalah para martir kebebasan yang tak dikenal, gugur di medan perang, dan dikebumikan tanpa pusara.
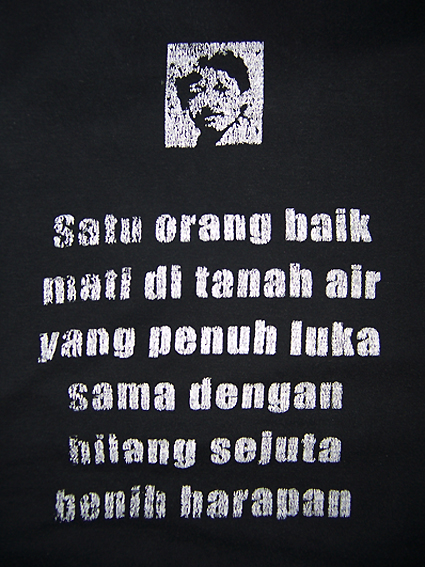
Pahlawan adalah para martir kebebasan yang tak dikenal, gugur di medan perang, dan dikebumikan tanpa pusara. (Munir Umar Thalib)
Wanita yang sempat menyayangkan mengapa nama suaminya justru “diabadikan” di negeri lain, bukan di tanah kelahiran suaminya sendiri inipun menambahkan, “Nilai-nilai yang diyakini dan hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang pejuang kebenaran tak perlu dikenang (dengan penghargaan, –ed).” Karena baginya, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan siapapun di muka bumi ini, entah dihargai atau tidak.
Peran Ganda Seorang Istri
Sepak terjangnya mengungkap dalang pembunuh sang suami yang hingga saat ini belum juga terungkap tuntas, tak putus dilakukannya. Di samping itu, ia adalah seorang single fighter yang berperan ganda; mendidik dan membesarkan anak-anak, serta menjadi ‘benteng pertama’ dalam mem-back up perjuangan suaminya. Tidak itu saja, bahkan (menurut sebuah sumber yang pernah saya baca) Suciwati bersama rekan-rekannya mendirikan taman kanak-kanak di Malang. Luar biasa, bukan? Tentu ketangguhan semacam ini patut diapresiasi bahkan ditiru wanita masa kini. Betapa wanita tidak selalu identik dengan sifat lemah dan tak berdaya. Kelembutan naluri tidak berarti berbanding lurus dengan kelemahan mental.
Fitrah wanita sebagai pendidik generasi yang menuntut kita memahami dunia anak-anak, bahkan tak jarang membuat kita perlu bertingkah seperti anak-anak, tak berarti membuat jiwa dan karakter kita kekanak-kanakan juga, bukan?
Menikah; Seni Menyatukan Frekuensi
Suciwati tidak pernah berjuang seorang diri, sebab istri-istri pejuang telah diwakilkan oleh banyak nama. Suciwati adalah salah satu potret wanita tangguh. Bahkan jauh sebelum Munir berjuang bersama istrinya, memperjuangkan sesuatu yang telah menjadi nafas dalam geraknya, Nabi Ibrahim juga telah berjuang bersama istrinya, Hajar. Memperjuangkan sebuah keyakinan, “Jika yang kita kerjakan ini adalah perintah Allah, niscaya kita takkan pernah disia-siakan oleh-Nya.”
Atau sebagaimana kebenaran abadi yang diperjuangkan Rasulullah bersama Khadijah, di masa-masa kritis awal mereka berdua berjuang dan bergerak. Atau sebagaimana istri Najmuddin Ayyub yang mencari suami yang sefrekuensi visi dengannya, hingga akhirnya –bi idznillah–, bermula dari kesamaan visi itulah lahir Shalahuddin Ayyub, Al-Fatihnya Palestina. Lalu ada juga istri Buya Hamka yang pernah mengingatkan suaminya untuk “menjauhi kursi penguasa” karena baginya amanah sebagai seorang penjaga masjid lebih utama di sisi Allah.
Menyinggung Suciwati, saya pun teringat istri Siyono (Allahu yarham), Mufida. Segepok “uang tutup mulut” dari aparat pemerintah atas kasus pembunuhan suaminya; imam masjid yang ditangkap tanpa surat izin penangkapan lalu pulang dalam kondisi nyawa telah meregang, ditolaknya mentah-mentah. Sebuah perjuangan mempertahankan izzah dan keyakinan yang patut diteladani.
Barangkali apa yang menjadi inspirasi dan nafas perjuangan Munir dan istrinya tidak sama dengan beberapa contoh figur teladan di atas. Tapi skenario hidup yang mereka alami serupa. Kehilangan seorang suami atau bahkan istri pejuang. Kehilangan nahkoda atau awak perjuangan. Kehilangan belahan jiwa yang dicintai, bahkan lebih dari sekadar belahan jiwa. Sebab nafas perjuangan mereka telah mengalir sehati sejiwa. Skenario semacam itu tentu berpotensi membuat oleng bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera yang berombak ganas. Namun sejak awal, mereka telah memilih mengikrarkan akad mitsaqan ghalizha di atas sebuah kesamaan frekuensi, keselarasan visi dan misi. Kesamaan frekuensi inilah yang menjadi benih awal timbulnya sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. In sya Allah.
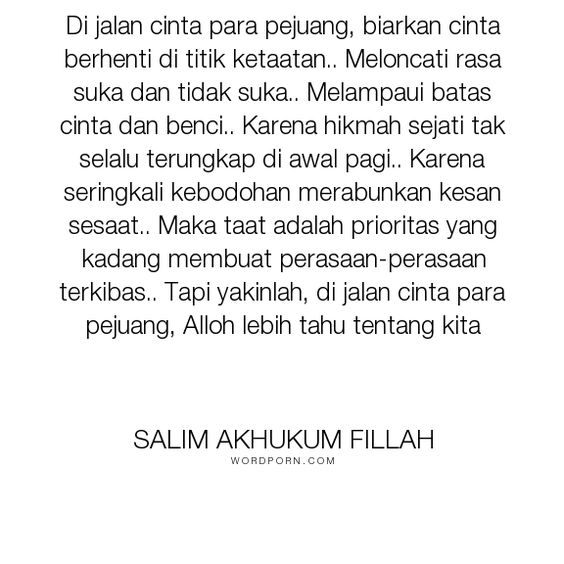
Kesamaan Tujuan adalah Titik Awal Keberangkatan
Bermodalkan rasa “klik” yang tumbuh dari kesibukan yang sama di dunia advokasi buruh, meski ia sendiripun telah menyadari konsekuensi jika hidup bersama Munir, Suciwati menerima pinangan aktivis HAM itu. Katanya, “Karena apa yang kami perjuangkan sama…”
Kesamaan tujuan dan ruang gerak inilah yang memang lebih mudah menumbuhkan ketenangan jiwa, karena kita paham apa yang partner hidup kita kerjakan, bagaimana lingkungan dan rekan-rekan kerjanya, serta yang lebih penting adalah memahami bagaimana risiko dan konsekuensi menjalani hidup bersamanya. Saya tidak mengatakan bahwa guru tidak cocok dengan dokter, atau relawan kemanusiaan tidak klop dengan pegawai kantoran karena atmosfer dan konsekuensi ruang gerak yang berbeda. Tapi yang ingin saya garisbawahi adalah kesetaraan ghoyyah (tujuan) dalam mengarungi bahtera pernikahan, agar pernikahan itu tak sekadar digadang-gadang keindahannya di dunia, namun abadi hingga surga.
Maka jika boleh merumuskan teori, jangan cari pasangan yang pasang gelarnya cuma sampai S2 (sehidup semati), ini jelas sangat kurang. Atau cuma S3 (sehidup semati seperjuangan), ini juga masih kurang. Tapi carilah yang S4 (sehidup semati sesurga seperjuangan), nah barangkali ini barulah lengkap. 🙂
Yaa Rabb, anugerahkanlah kepada kami keshiddiqan dalam ghayyah, keikhlasan dalam melangkah, serta kesabaran dalam memperjuangkan Jannah. Aamiin.
Best regards,
Nina dan remah-remah pikirannya 😉

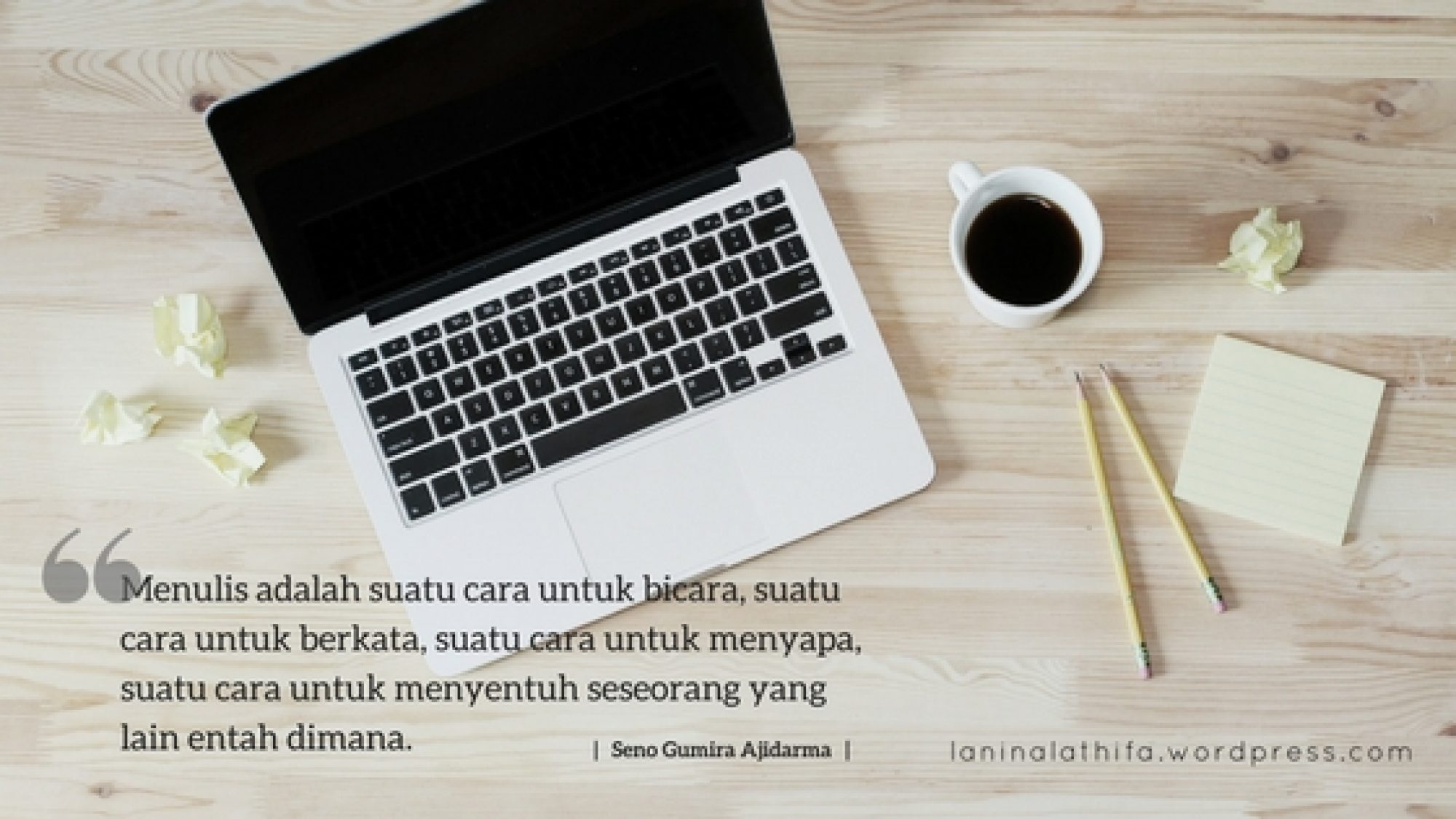
Reblogged this on Pemulung Hikmah.
SukaSuka
Reblogged this on el-safira.
SukaSuka