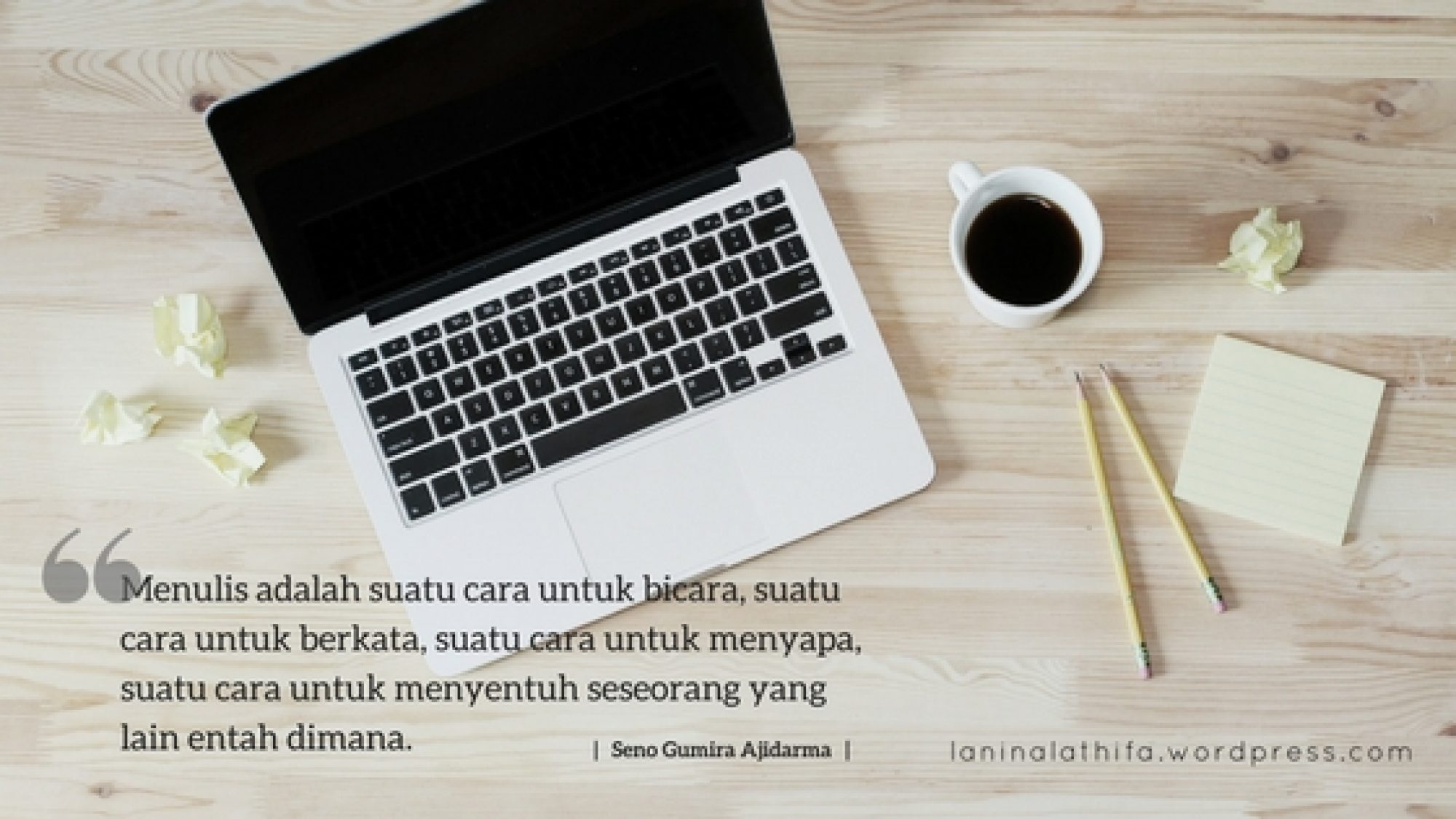“Semua orang, meski tanpa minus ataupun silindris, selalu melihat sesuatu dengan kacamata masing-masing.” (Rahne Putri)
Bukan. Cerita ini bukan tentang kacamata yang diperjualbelikan di pinggir-pinggir jalan. Ini tentang kacamata kita. Bukan tentang gangguan penglihatan. Ini tentang cara pandang kita. Bukan soal bicara empat mata, karena aku ingin mengajakmu bicara dari hati, tempat bersemayamnya segala pandangan mata.
Sebenarnya ini kisah tentang seorang lelaki yang memilih hidup sendiri, sampai ia bertemu mati. Orang-orang di sekelilingnya, entah dengan atau tanpa kacamata, memandangnya sebagai lelaki penyendiri yang aneh, lengkap dengan kacamata tuanya. Lelaki renta itu selalu menampakkan diri di waktu pagi, kemudian kembali di saat matahari memilih sembunyi.
“Bapak kok betah sih hidup sendiri sampai tua begini?” Celetuk tetangga samping kiri.
“Keluarga Bapak pergi kemana kok sampai Bapak hidup sebatang kara begini?” Singgung tetangga samping kanan.
“Saya tidak pernah merasa hidup sendiri. Setiap hari saya justru selalu merasa diawasi.” Jawab Pak Yoyok singkat.
“Saya yang pergi menjauhi keluarga, istri, anak-anak, dan sahabat. Saya sendiri yang memilih pergi.” Imbuh lelaki tua berkacamata itu.
“Lho, kenapa Pak? Boleh saya tahu?” Tetangga kiri begitu ingin tahu.
“Maaf Pak, saya hanya ingin menyimpan sendiri alasannya. Khawatir jika kisah saya nanti sedikitpun tidak memberi manfaat buat Bapak. Makanya selama ini saya memilih diam. Menanti saat yang tepat untuk bicara. Yaitu di tengah kesendirian. Bercerita sepuas-puasnya dengan Dzat yang tak pernah membocorkan rahasia.”
Pak Yoyok mengucap salam, dan berlalu meninggalkan tetangga kanan dan kirinya.
“Seandainya mereka tahu bahwa aku hidup sendiri untuk sebuah alasan. Aku hanya lelaki tua mantan narapidana. Keluarga besar belum bisa ikhlas menerima kepulanganku. Tetangga sekeliling rumah kecilku juga demikian. Masih menyimpan dendam kesumat yang entah kapan surut. Memaksa istri dan anak-anak menutup telinga rapat-rapat mendengar olokan yang sebenarnya sangat menyakitkan, bukan buatku, tapi buat mereka, istriku, anak-anakku. Hanya saja aku pilih untuk dipendam. Aku tak ingin anak-anakku tumbuh berkembang dengan olok dan cacian tentang Ayah mereka. Tentang sosok yang seharusnya mereka banggakan.
Aku pun memilih pergi (lagi) untuk sebuah alasan. Menjaga mereka yang kucintai disana. Sebab kadang, jarak adalah cara untuk menjaga. Hanya saja, orang-orang itu tidak (belum) mengerti. Masing-masing orang bertindak karena sebuah alasan. Entah itu mampu mereka pahami, atau tidak sama sekali. Sejujurnya aku, benar-benar ingin berubah, meski mereka sudah lebih dulu ragu dan menolak diriku yang baru. Dan jika suatu hari nanti aku pergi mati, aku ingin pergi dengan sebaik-baik kepergian. Biarlah istri dan anak-anakku aman dalam penjagaan-Nya, bukan penjagaanku. Seperti yang sudah-sudah, saat aku menyia-nyiakan mereka dengan segala perilaku burukku. Dia-lah yang selalu menjaga keluarga kecilku di rumah. Semoga, ada kenangan manis yang masih di terekam di memori jangka panjang anak-anakku. Setidaknya, aku pergi sebagai Ayah yang baik.”
Lelaki tua berkacamata itupun benar-benar pergi mati. Kacamatanya tertinggal di atas meja. Tertinggal pula kacamata-kacamata tentang dirinya, yang penuh prasangka tentang siapa dan bagaimana dirinya.
“Manusia adalah pengacara yang hebat untuk kesalahan diri sendiri, tetapi berubah menjadi hakim yang mahsyur untuk kesalahan orang lain.” (Tere Liye)